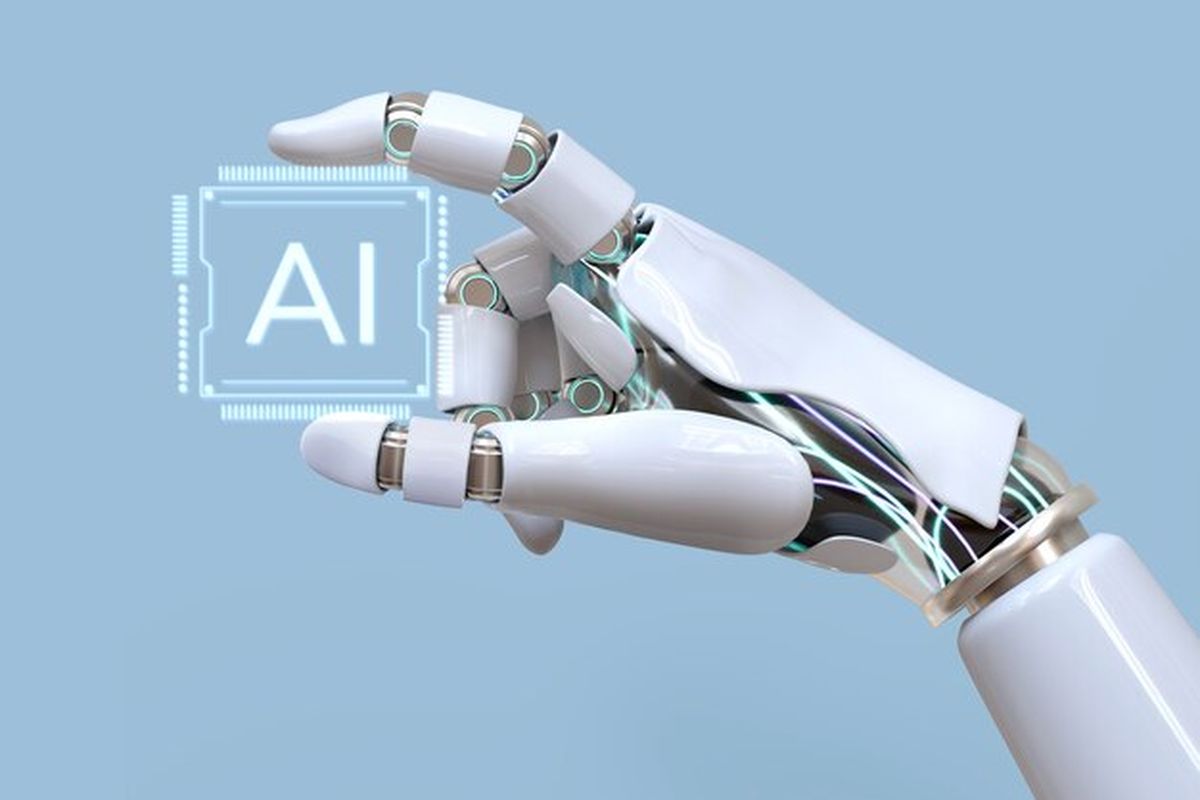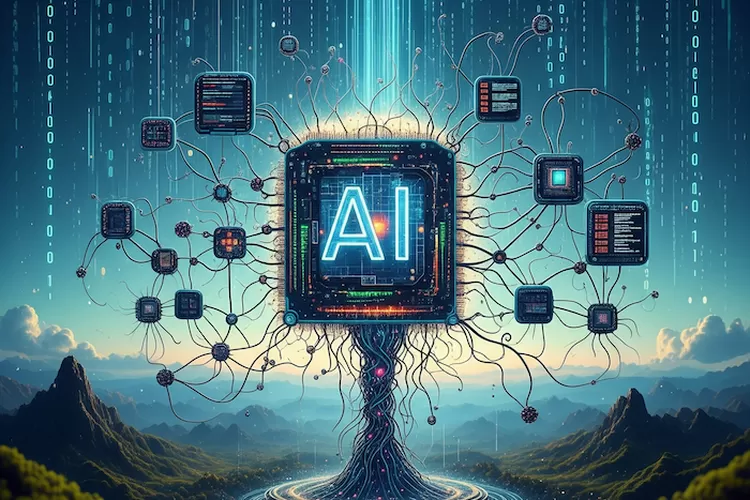Pendahuluan
Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, satu hal yang sering terlupakan adalah inklusivitas bahasa lokal. Indonesia punya lebih dari 700 bahasa daerah, namun teknologi AI yang digunakan sehari-hari masih sangat terpusat pada Bahasa Indonesia, dan lebih parahnya lagi—bahasa Inggris. Pertanyaannya: apa sebenarnya kebutuhan komunitas bahasa lokal terhadap teknologi ini?
Sebuah survey nasional yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada dan didukung oleh Kemendikbudristek baru-baru ini mencoba menjawab pertanyaan itu. Mereka mewawancarai ribuan responden dari komunitas bahasa di berbagai provinsi—dari Aceh, Kalimantan, hingga Papua.
Hasilnya sangat menarik dan bisa menjadi arah baru pengembangan AI lokal yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan konteks budaya di Indonesia.
Hasil Survey: Terjemahan Otomatis Jadi Prioritas Utama
Dalam survei tersebut, 68% responden menyatakan bahwa terjemahan otomatis dari dan ke bahasa lokal merupakan fitur paling dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa terbatas dalam mengakses informasi digital karena keterbatasan bahasa.
Contohnya, di wilayah Maluku, banyak siswa kesulitan memahami materi daring karena hanya tersedia dalam Bahasa Indonesia atau Inggris. Hal ini mempersulit proses belajar mandiri dan memperlebar kesenjangan digital. Dengan adanya AI yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa lokal seperti Ambon, Ternate, atau Kei, maka akses pendidikan akan jauh lebih merata.
Lebih dari sekadar komunikasi, terjemahan AI juga dipandang penting untuk melestarikan bahasa daerah. Banyak bahasa lokal yang nyaris punah karena tidak lagi digunakan dalam ruang publik atau media digital. AI bisa hadir sebagai alat dokumentasi sekaligus penghidupan kembali bahasa tersebut melalui integrasi ke aplikasi mobile dan asisten virtual.
Retrieval & Penelusuran Berbasis Bahasa Lokal
Selain terjemahan, 43% responden menyatakan kebutuhan terhadap retrieval informasi berbasis bahasa lokal. Artinya, masyarakat ingin bisa mencari informasi di mesin pencari menggunakan bahasa daerah mereka sendiri—sebuah fitur yang masih langka saat ini.
Bayangkan masyarakat Toraja bisa mencari info tentang cuaca, harga pupuk, atau jadwal vaksin hanya dengan menggunakan bahasa Toraja. Ini akan mendorong adopsi teknologi oleh kalangan lansia dan masyarakat pedesaan yang tidak terbiasa menggunakan Bahasa Indonesia formal atau bahasa asing.
AI yang mampu memahami perintah suara atau teks dalam bahasa lokal bisa membuka peluang besar untuk inklusi digital. Ini tidak hanya penting dalam sektor pendidikan, tapi juga di bidang kesehatan, administrasi, dan layanan publik.
Beberapa komunitas juga menyarankan agar pencarian bisa dilakukan secara multibahasa campuran (misalnya: Bahasa Bugis + Bahasa Indonesia), seperti yang biasa terjadi dalam percakapan sehari-hari masyarakat di Sulawesi atau Kalimantan.
Kekhawatiran terhadap Privasi & Etika Data Bahasa
Namun tidak semua tanggapan bernada optimistis. Sekitar 35% responden menyatakan kekhawatiran bahwa penggunaan AI untuk pengumpulan dan pelatihan data bahasa lokal dapat menyebabkan komodifikasi budaya tanpa izin.
Ada rasa takut bahwa teknologi justru akan “menyedot” bahasa lokal untuk kepentingan korporasi, tanpa adanya keterlibatan komunitas dalam prosesnya. Hal ini sangat penting mengingat banyak budaya Indonesia memiliki nilai sakral terhadap bahasa.
Oleh karena itu, masyarakat mendorong agar ada regulasi ketat soal etika pelatihan data. Mereka juga ingin ada transparansi soal bagaimana data bahasa lokal digunakan, apakah mereka mendapatkan akses hasilnya, dan apakah ada keuntungan finansial atau pendidikan untuk komunitas asal.
Salah satu usulan menarik adalah pendirian bank data bahasa komunitas, di mana komunitas sendiri yang memiliki kontrol atas data bahasa mereka, dan bekerja sama dengan institusi akademik atau pemerintah.
Referensi
Penutup: AI yang Inklusif Harus Mulai dari Akar Budaya
Teknologi tidak boleh hanya menyasar mereka yang fasih dan terdidik. AI di Indonesia harus punya misi kultural: memudahkan semua orang—dari anak-anak Sumba, petani Minang, hingga nelayan di Halmahera—untuk ikut dalam dunia digital, tanpa harus meninggalkan bahasa dan budaya mereka sendiri.
Hasil survey ini jadi momentum penting bagi pengembang lokal, start-up AI, dan pemerintah untuk menyusun roadmap teknologi yang lebih adil. Di era di mana teknologi makin canggih, nilai-nilai lokal tidak boleh tertinggal. Sebaliknya, justru bisa jadi kekuatan utama Indonesia di masa depan.